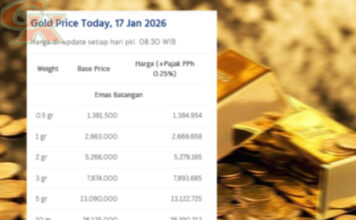Pikiran layak mendapatkan tugas yang sesuai dengan kekuatannya
JAKARTA, GESAHKITA COM—–
Jika Anda belum membaca karya agung modernis Robert Musil yang belum selesai, The Man Without Qualities , Anda mungkin setuju bahwa judulnya bagus.
Jika Anda sudah membacanya, saya yakin Anda setuju, karena novel tersebut kembali secara obsesif ke tema tentang bagaimana tokoh utamanya, Ulrich, tidak bisa benar-benar menata tindakannya, atau lebih mendasar lagi kepribadiannya menjadi utuh. Namun saya menemukan judul yang lebih baik. Saya pikir Musil seharusnya memberi judul novelnya The Man Without Philosophy.
Begitu paragraf pembuka artikel ditulis Agnes Callard di laman UnHerd yang mana diketahui ia adalah Associate Professor filsafat di University of Chicago, lengkap nya dibawah ini gesahkita alihkan bahasa nya untuk kita semua.
Saya mengakui, dalam menawarkan perbaikan ini, bahwa selama novel Ulrich secara eksplisit menganut filsafat hidup; lebih jauh, ia bahkan menciptakan namanya sendiri untuk filsafat ini, “esaiisme”.
Esaiisme adalah cara hidup yang ekspresi karakteristiknya adalah peregangan refleksi baru dan mendalam, “mengeksplorasi sesuatu dari banyak sisi tanpa mencakupnya”.
Penulis esai menjalani kehidupan dengan pengamatan yang bijaksana. Ulrich menjalani kehidupan itu, dan begitu pula Musil, yang jauh lebih tertarik untuk mengisi novelnya dengan pengamatan yang bijaksana daripada dengan salah satu dari penemuan-penemuan biasa dari plot atau pengembangan karakter.
Ulrich menolak untuk menjadi “orang yang pasti di dunia yang pasti”, dan sebaliknya memanfaatkan kapasitas pikirannya yang tak berdasar untuk mengevaluasi ulang untuk meniru perubahan tak terbatas dari “setetes air di dalam awan”. Ulrich menggambarkan hubungannya dengan ide-ide: “mereka selalu memprovokasi saya untuk menggulingkan mereka dan menempatkan orang lain pada tempatnya.”
Bagi Ulrich, seperti halnya bagi Musil, “hanya ada satu pertanyaan yang layak dipikirkan, pertanyaan tentang cara hidup yang benar.” Bukankah itu, pada hakikatnya, merupakan proyek filosofis? Ya.
Namun, ada alasan yang baik untuk menegaskan bahwa Ulrich adalah orang yang tidak memiliki filsafat, yaitu fakta bahwa baik Musil maupun Ulrich menegaskannya, berulang kali. Ulrich mengakui bahwa dalam kesulitannya, “ia hanya bisa beralih ke filsafat” tetapi masalahnya adalah bahwa filsafat “tidak menarik baginya”. Berulang kali: “ia bukanlah seorang filsuf.” Ia mengambil “pandangan yang agak ironis tentang filsafat”, karena, beberapa dekade sebelum novel dimulai, ia telah putus asa untuk benar-benar menemukan cara hidup yang benar: “pikiran kita tidak dapat diharapkan untuk tetap tegak tanpa batas waktu, seperti halnya tentara yang berparade di musim panas; berdiri terlalu lama, mereka akan langsung pingsan.” Hasilnya adalah bahwa “ia selalu terprovokasi untuk berpikir tentang apa yang sedang ia amati, namun pada saat yang sama dibebani dengan rasa malu tertentu untuk berpikir terlalu keras”.
Berpikir keras masuk akal jika Anda menginginkan jawaban; berpikir keras kurang masuk akal jika imbalan tertinggi yang Anda harapkan dari usaha intelektual Anda adalah kejutan. Perbedaan antara kehidupan filosofis dan esais adalah bahwa kehidupan filosofis bertujuan pada pengetahuan, sedangkan kehidupan esais bertujuan pada hal-hal baru.
Respons positif yang menjadi ciri khas esais adalah: “Saya belum pernah memikirkannya seperti itu sebelumnya”; musuh utama penulis esai adalah kebosanan. Ulrich “selalu melakukan sesuatu selain dari apa yang ingin ia lakukan” untuk memastikan ketidakpastiannya, bahkan pada dirinya sendiri.
Penulis esai adalah makhluk yang responsif dan reaktif, selalu menyadari cara standar dalam memandang sesuatu, dan selalu waspada terhadap jalan yang paling mudah menuju beberapa sudut pandang alternatif.
Dalam cerita Musil, kehidupan seorang penulis esai adalah kehidupan yang penuh siksaan, karena dalam kehidupan inilah filsafat tidak hanya absen, tetapi lebih khusus lagi, hilang.
Ketika Anda melihat Ulrich, yang Anda lihat, pada awalnya, hanyalah seorang intelektual fasih yang tersenyum pada refleksi cerdasnya sendiri; tetapi akhirnya Anda melihat bahwa di samping pria yang ceria dan percaya diri ini, ada, seperti yang disebut Musil, “Ulrich kedua”.
Ulrich kedua, “yang kurang terlihat dari keduanya”, sedang “mencari formula ajaib, pegangan yang mungkin untuk dipahami, pikiran sejati dari pikiran, bagian yang hilang,” tetapi dia terdiam, tidak dapat menemukan kata-kata untuk mengekspresikan dirinya. Musil mengatakan pria ini “mengepalkan tangannya karena kesakitan dan amarah”. Ulrich sang filsuf terperangkap di dalam Ulrich sang penulis esai.
Musil sendiri menolak pekerjaan akademis di bidang filsafat, yang membuat keluarganya sangat kesal, demi menulis buku berisi pengamatan yang mendalam. Buku tersebut, dan karakter Ulrich, menunjukkan kepada kita bagaimana rasanya menjadi seorang pemikir tanpa tujuan: selalu menganggur meskipun aktivitas intelektualnya tak henti-hentinya dan tak pernah berhenti.
Ulrich adalah seorang penggoda wanita yang hubungannya dengan wanita serupa dengan, dan karenanya memberi kita wawasan tentang, hubungannya dengan ide-ide. Di awal novel, ia menggambarkan suatu malam dengan salah seorang kekasihnya menggunakan dua gambaran: yang pertama adalah “halaman yang disobek” dari sebuah buku. Malam itu, meskipun menyenangkan, tidak terhubung dengan narasi yang lebih besar. Ulrich tidak mencari istri, atau memulai sebuah keluarga; ia hanya suka berada di dekat mereka, sampai ia tidak menginginkannya lagi dan ini berarti bahwa malam-malam romantisnya tidak akan berjalan sesuai rencana, seperti serangkaian liburan.
Gambaran kedua, yang bahkan lebih mencolok, adalah gambaran tentang sebuah tableau vivant: sebuah drama yang membeku, di mana para aktor berpose tanpa bergerak untuk menciptakan kembali sebuah adegan terkenal. Bayangkan, misalnya, seorang aktris yang memainkan peran Medea yang berdiri di atas anak-anaknya sambil memegang pisau.
Musil menggambarkan momen seperti itu sebagai “penuh makna batin, digariskan dengan tajam, namun, secara keseluruhan, sama sekali tidak masuk akal”. Tableau vivant tidak masuk akal karena Anda tidak akan pernah memegang pisau seperti itu, diam, siap, melayang di atas seseorang: posisi itu hanya masuk akal dalam konteks posisi lain, yang terintegrasi sebagai gerakan.
Hal Ini adalah deskripsi yang tepat tentang apa yang terjadi ketika ide dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang hanya cocok untuknya jika Anda tidak menghilangkan kemungkinan untuk “mencakup beberapa pokok bahasan secara menyeluruh”. Ketika Anda memotong cinta manusia, atau pikiran manusia, menjadi beberapa bagian, efeknya mirip dengan memotong tubuh manusia menjadi beberapa bagian: mengerikan.
“Saya takut kalau saya mencarinya dengan saksama, saya akan menemukan bahwa sebenarnya tidak ada jawaban di sana.”
Musil bertempur dalam Perang Dunia Pertama; selama Perang Dunia Kedua, Nazi melarang buku-bukunya dan dia tinggal di pengasingan bersama istrinya yang Yahudi di Swiss.
Dia meninggal pada tahun 1942, meninggalkan The Man Without Qualities , yang telah dia revisi dengan obsesif selama beberapa dekade, belum selesai. Fakta yang luar biasa tentang novel itu adalah Ulrich, alter ego Musil, tidak menginjakkan kaki di kedua perang itu.
Novel itu dibuka pada bulan Agustus 1913, dan dalam lebih dari seribu halaman, novel itu tidak pernah berhasil melintasi 11 bulan hingga dimulainya Perang Dunia Pertama. Musil tahu sesuatu tentang kekejaman perang modern yang tidak manusiawi dan kebrutalan penindasan totaliter, tetapi itu bukan pokok bahasannya.
Sebaliknya, dia ingin melaporkan, secara langsung, tentang apa yang telah dia lihat sebelumnya, ketika masa-masa itu seharusnya baik, sebuah kesadaran yang begitu mengganggu sehingga bahkan dua perang dunia berikutnya tidak dapat mengalihkan perhatiannya darinya: “hanya ada sesuatu yang hilang dalam segala hal.”
Di masa-masa sulit, tujuan jangka pendek memenuhi bidang pandang Anda; justru ketika keadaan sedang baik, Anda berada dalam posisi untuk mengambil langkah mundur dan menyadari bahwa tujuan jangka panjang yang besar, tujuan yang seharusnya menyatukan semuanya, justru telah hilang.
Saya membaca The Man Without Qualities pertama kali saat saya masih di sekolah pascasarjana jurusan Klasik, dan dalam waktu setahun, saya meninggalkan program itu dan beralih ke filsafat. Mengapa, mengingat saya telah melahap teks-teks filsafat sejak sekolah menengah, saya tidak mengambil jurusan filsafat di perguruan tinggi, atau menekuninya setelah kuliah?
Saya rasa saya tidak dapat mengatakannya seperti ini saat itu, tetapi: Saya takut. Ketakutan itu sebagian adalah rasa tidak aman tentang diri saya sendiri bahwa saya tidak akan memenuhi syarat, bahwa saya tidak memiliki apa pun untuk disumbangkan, bahwa saya tidak layak untuk menapaki koridor filsafat yang terhormat tetapi bagian lainnya, bagian yang lebih dalam, adalah ketakutan tentang filsafat.
Saya takut jika saya mencari dengan saksama, saya akan menemukan bahwa sebenarnya tidak ada jawaban di luar sana. Selama saya tidak pernah mencoba menemukan cara hidup yang benar, saya tidak dapat dengan pasti mengatakan itu tidak ada.
Saya tidak mengklaim bahwa Musil meyakinkan saya bahwa itu ada. Tidak, apa yang diberikan The Man Without Qualities kepada saya adalah pandangan yang jelas dan mengerikan tentang kehidupan pengamatan yang penuh pertimbangan; Musil adalah hantu Natal masa depan saya.
Entah bagaimana, saya harus menemukan sumber daya dalam diri saya untuk percaya bahwa penyelidikan itu mungkin, baik bagi manusia secara umum, dan bagi saya secara khusus, karena, meskipun prospek kegagalan itu menakutkan, saya baru saja melihat sesuatu yang lebih menakutkan.
Anda dapat menganggap pikiran memiliki tombol putar yang biasanya diputar ke bawah, kecuali pada saat-saat ketika kita perlu memecahkan masalah tertentu, tetapi bahkan saat itu, kita hanya memutarnya sedikit. Apa yang akan terjadi jika Anda menyetelnya ke maksimum, sepanjang waktu? Pikiran akan mencerna segalanya melalui pembenaran diri kita yang biasa, melalui keangkuhan akan keniscayaan yang melekat pada kebiasaan dan adat istiadat kita, melalui perancah tipis nalar yang menyatukan kehidupan.
Pikiran seperti itu akan menjadi, seperti yang pernah dijelaskan Ulrich tentang dirinya sendiri, “sebuah mesin untuk devaluasi kehidupan yang tak henti-hentinya”. Satu-satunya cara untuk menghindari hasil ini adalah dengan memberi pikiran tugas yang sesuai dengan kekuatannya, dengan memberinya jenis pertanyaan yang dapat kita pikirkan dengan keras tanpa rasa malu.
Tetapi itu memerlukan harapan untuk sampai pada jawaban. Ini adalah salah satu cara untuk berpikir tentang filsafat: ruang yang aman untuk operasi pikiran yang tidak terkekang.
Agnes Callard adalah Associate Professor filsafat di University of Chicago. Sumber UnHerd, alih bahasa gesahkita.