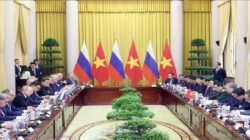Bagaimana Vladimir Putin dan Xi Jinping mendefinisikan demokrasi
Para otokrat seperti Xi Jinping dan Vladimir Putin takut terhadap demokrasi, namun berusaha keras untuk menampilkan diri mereka sebagai pemimpin yang demokratis.
JAKARTA, GESAHKITA COM—Di Rusia pada masa Putin, otokrasi tidak selalu dipandang tidak sesuai dengan demokrasi. Di Tiongkok pada masa pemerintahan Xi, nilai-nilai demokrasi Barat dicap sebagai nilai-nilai borjuis dan merupakan penghalang bagi keadilan pemerintahan komunis. Namun, dengan menentang hak asasi manusia “dalam pengertian Barat”, para diktator ini berusaha menyembunyikan ketidakpedulian mereka terhadap hak asasi manusia yang benar-benar universal.
Tak lama setelah Xi Jinping terpilih kembali sebagai kepala negara Tiongkok pada tahun 2022 – dengan suara 2.950 berbanding nol – Menteri Luar Negeri Tiongkok Qin Gang mengkritik Presiden AS Joe Biden karena mengontekstualisasikan peristiwa tersebut sebagai bagian dari pertarungan antara negara-negara demokrasi Barat dan otokrasi non-Barat . . Gang menyatakan bahwa Tiongkok, bersama dengan Rusia di bawah Vladimir Putin, “berkomitmen untuk mempromosikan dunia multipolar dan demokrasi yang lebih besar dalam hubungan internasional.”
Namun, tidak ada politisi yang bisa mempercayai kata-katanya. Karier Gang didasarkan pada kesetiaannya kepada Xi, sehingga ia mendapat promosi menjadi anggota dewan negara bagian. Sementara itu, Biden berharap dapat memberikan rasa takut yang eksistensial pada kampanye pemilihannya kembali melawan Donald Trump. Termotivasi oleh politik negara masing-masing, tidak ada yang menceritakan kisah lengkapnya.
Meskipun tradisi demokrasi modern terkait erat dengan Eropa, berasal dari Athena kuno dan berkembang pada masa Pencerahan, adalah salah jika berasumsi bahwa pemerintahan perwakilan pada dasarnya merupakan konsep Barat, dan secara eksistensial tidak sesuai dengan masyarakat non-Barat. Keyakinan seperti itu mudah dibantah oleh keberhasilan negara-negara demokrasi modern seperti Jepang dan Korea Selatan – belum lagi bukti arkeologis mengenai struktur masyarakat yang demokratis di India, Meksiko, dan belahan dunia lain yang jauh dari pantai Yunani.
Pada saat yang sama, patut dipertimbangkan mengapa Xi dan Putin, dua pemimpin otokratis yang menindas rakyatnya agar tetap berkuasa, melewati rintangan logis dan linguistik untuk menampilkan diri mereka sebagai pemimpin perwakilan negara-negara demokratis. Strategi yang tampaknya kontradiktif ini tidak hanya berfungsi untuk menetralisir oposisi internal mereka dengan memberikan ilusi kepada masyarakat tentang lembaga politik, namun juga untuk memberdayakan posisi mereka sendiri. Pada akhirnya, Xi dan Putin mendefinisikan demokrasi bukan sebagai pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, namun sebagai pemerintahan yang bertindak atas nama rakyat untuk melindungi (seharusnya) kepentingan mereka.
Demokrasi di Rusia
Sikap Putin terhadap demokrasi “gaya Barat” berakar pada sejarah Rusia karena negara tersebut telah lama diidentifikasi sebagai negara yang berbeda dari Barat. Ketika revolusi demokrasi menggulingkan monarki di Eropa, para tsar bersikukuh bahwa perkembangan serupa tidak akan pernah terjadi di tanah Rusia. Keyakinan mereka tidak hanya didasarkan pada pelestarian diri, tetapi juga tradisi kuno dalam filsafat dan sastra Rusia. Para pemikir terkemuka Rusia telah menghabiskan waktu berabad-abad memperdebatkan apakah Rusia merupakan negara Eropa, Asia, atau negara lain. Di masa yang penuh ketidakpastian ini, kelompok konservatif mulai melihat tsar – dan, lebih jauh lagi, kekuasaan absolut yang dimiliki individu tersebut – sebagai landasan identitas nasional dan demokrasi perwakilan sebagai musuh eksistensialnya.
Cara berpikir seperti ini, yang ditindas di bawah Uni Soviet, muncul kembali di masa pemerintahan Putin. Menurut Kathryn Stoner, peneliti senior di Freeman Spogli Institute for International Studies dan direktur Pusat Demokrasi, Pembangunan, dan Supremasi Hukum, hal ini bahkan dapat menjelaskan keberhasilan politiknya. Seperti yang dia nyatakan dalam artikel yang ditulis untuk Journal of Democracy :
“Para sejarawan mengatakan kepada kita bahwa kita tidak perlu terkejut bahwa Rusia telah kembali ke sistem otokrasi yang represif, dan hal ini bukan disebabkan oleh buruknya tata kelola pemerintahan, namun buruknya lahan yang menjadi tempat benih-benih demokrasi ditaburkan. Mengingat kurangnya pengalaman Rusia dalam menghadapi liberalisme, ditambah dengan industrialisasi yang terlambat dan komunisme yang sudah berjalan selama tujuh dekade, kita tidak boleh bertanya mengapa transisinya ke arah politik yang lebih liberal gagal, namun mengapa kita mengharapkan negara tersebut berhasil. Secara statistik, […] sebagian besar negara otokrasi bertransisi ke berbagai bentuk otokrasi dibandingkan ke pemerintahan yang representatif dan akuntabel.”
Visi Putin terhadap Rusia dan negara Rusia berubah seiring memburuknya hubungannya dengan Barat. Mewarisi pemerintahan perwakilan yang rentan namun menjanjikan dari Boris Yeltsin, Putin menghabiskan masa jabatan presiden pertamanya untuk membangun kembali hubungan dengan negara lain. Hubungan baru ini baru memburuk setelah pertumbuhan ekonomi Rusia melambat dan peringkat persetujuannya anjlok. Seperti para tsar yang terancam punah sebelum dirinya, mantan perwira KGB ini menyebut lawan-lawannya yang terpilih secara demokratis sebagai musuh, dan mengasosiasikan identitas negara yang selama ini sulit dipahami dengan dirinya sendiri.
Sejak terpilih kembali pada tahun 2012, tulis Stoner, Putin “menampilkan identitas nasional Rusia sebagai identitas nasional yang tidak liberal, konservatif secara sosial, dan non-‘Anglo Saxon,’ yang sangat kontras dengan Amerika Serikat dan Inggris.” Ketidakpercayaannya terhadap budaya Barat lebih dari sekadar politik identitas: “ Cita-cita liberal dan tuntutan terhadap pemilu yang bebas dan adil bukanlah sesuatu yang berasal dari bangsa Rusia, melainkan impor jahat dari ‘Barat’.”
Meskipun Putin mungkin secara terbuka mendefinisikan Rusia sebagai negara yang tidak liberal, Anda tidak akan mendengar dia menyebut dirinya seorang otokrat. Hal ini karena pemilu – yang masih diadakan meskipun sebagian besar negara meragukan integritas pemilu – berfungsi sebagai sarana untuk berpura-pura mendukung pemerintahannya. Terpilih secara demokratis atau tidak, Putin mengaku bertindak demi kepentingan rakyat Rusia. Mereka yang tidak setuju, menurutnya, telah dicuci otak oleh pengaruh asing.
Demokrasi di Tiongkok
Di Tiongkok, sikap terhadap pemerintahan perwakilan Barat ditafsirkan melalui kacamata Marxisme dan Maoisme. Dalam serangkaian artikel yang diterbitkan di surat kabar harian PKT, People’s Daily, yang secara ringkas berjudul “Tanya Jawab tentang Kajian Pemikiran Xi Jinping tentang Sosialisme dengan Karakteristik Tiongkok di Era Baru” dan disetujui secara pribadi oleh Xi, Ketua mengartikulasikan sikap-sikap ini dalam mungkin istilah yang paling jelas.
Dalam salah satu artikelnya, Xi menjelaskan mengapa Tiongkok harus mengambil sikap menentang “apa yang disebut sebagai ‘nilai-nilai universal’ Barat.” Sebagai seorang Marxis, ia percaya bahwa sejarah peradaban bermuara pada pertarungan antar kelas ekonomi, dengan revolusi yang mengubah masyarakat dari feodalistik menjadi demokratis dan komunis hingga semua bentuk pemerintahan terpusat dibubarkan.
“Sementara tahap ‘otokrasi feodal’ dikalahkan oleh tahap revolusi borjuis yang lebih progresif, tahap liberalisme borjuis pada gilirannya telah, atau seharusnya, dikalahkan oleh sosialisme Marxis,” kata sosiolog Massimo Introvigne kepada Big Think.
Ia menambahkan bahwa selama revolusi borjuis, nilai-nilai seperti kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia bersifat progresif. “Namun, dalam kerangka teori sejarah dialektis Marxis, nilai-nilai yang sama, yang dulunya progresif, menjadi reaksioner pada tahap sejarah berikutnya.”
Menuduh AS dan negara-negara Barat lainnya mempromosikan nilai-nilai khusus budaya mereka sebagai sesuatu yang universal, Xi melihat Tiongkok sedang diserang oleh kekuatan imperialis. Para pejabat Tiongkok telah berulang kali menegaskan bahwa Barat tidak percaya pada retorika mereka sendiri, dan merujuk pada sejarah rasisme sistemik dan operasi militer yang membawa bencana. Daripada kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia, Xi lebih memilih berbicara tentang nilai-nilai universal seperti perdamaian, pembangunan, dan keadilan.
Tidak mengherankan, kelompok non-komunis tidak menganggap argumen Xi meyakinkan. “Ini adalah alasan semua rezim totaliter yang menolak memberikan hak asasi manusia, kebebasan, dan demokrasi kepada korbannya,” komentar Introvigne. “Mereka menyatakan bahwa ini adalah nilai-nilai ‘Barat’ dan tidak dapat diterapkan secara universal. Kata-kata Xi Jinping sangat menyentuh telinga semua diktator di dunia, dan inilah sebabnya mereka mendukung Tiongkok di PBB ketika catatan hak asasi manusia mereka yang sangat rendah dikecam.”
Semangat hukum
Bahkan sebelum Mao Zedong mendirikan Republik Rakyat Tiongkok, para pemikir Tiongkok memandang masyarakat dan kebutuhan politik mereka berbeda dengan masyarakat Barat. Penerjemah dan penulis akhir abad ke-19, Yan Fu, yang dikenal karena terjemahan teks-teks seperti On Liberty karya John Stuart Mill dan Spirit of the Laws karya Baron de Montesquieu , menulis bahwa meskipun demokrasi sangat penting bagi keamanan Tiongkok, jenis sistem yang digunakan di Eropa dan AS tidak bisa begitu saja dipindahkan ke Timur Jauh. Penyesuaian harus dilakukan karena beragamnya sejarah, budaya, dan kepekaan spiritual di wilayah tersebut.
Ada benarnya hal ini. Tidak ada satu model demokrasi pun yang dapat diterapkan dengan mudah antar negara. Bahkan di masyarakat Barat, demokrasi berkembang secara berbeda berdasarkan sejarah dan budaya suatu negara, seperti di Amerika Serikat dan Inggris. Hal yang sama juga berlaku di negara demokrasi Asia seperti Jepang dan Taiwan.
Penting juga untuk menyadari bahwa budaya Barat tidak memonopoli pemikiran demokrasi. Studi mengenai perbandingan pemerintahan, khususnya pemerintahan di negara-negara berkembang, dapat membantu memperbaiki keraguan ini.
Namun, pengakuan atas kebenaran ini tidak boleh menjadi alasan atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Rusia dan Tiongkok saat ini.
Di zaman di mana masyarakat Barat berusaha untuk melupakan, mengubah, dan meminta maaf atas masa lalu imperialis mereka, kita tergoda untuk menyerah pada gagasan yang tampaknya benar secara politis bahwa budaya yang berbeda dapat mendefinisikan demokrasi sesuai pilihan mereka. Sebenarnya, demokrasi mensyaratkan kekuasaan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Tanpa memenuhi persyaratan dasar tersebut, definisi lain apa pun – termasuk definisi pemerintah yang bertindak atas nama warga negaranya – dapat diubah untuk membenarkan pelanggaran hak asasi manusia.
Saat Introvigne menyimpulkan:
“PKT mungkin bersikeras bahwa tidak ada kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia ‘dalam pengertian Barat’ di Tiongkok, dan bahwa kata-kata ini memiliki arti yang berbeda dalam tradisi dan sistem politik Tiongkok (atau Rusia, atau Arab). Namun, hal inilah yang disangkal oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan teori hak asasi manusia modern, setelah Nazi juga mengklaim bahwa hak asasi manusia tidak bersifat universal dan bahwa Jerman mempunyai tradisi yang berbeda.
“ Tidak ada hak asasi manusia ‘Barat’ atau ‘Timur’. Yang ada hanyalah hak-hak yang harus dinikmati manusia sebagai manusia, yang berakar pada sifat umum manusia dan bukan pada tradisi sejarah atau sistem politik. Entah mereka dihormati atau tidak. Xi Jinping mengatakan kepada dunia bahwa Tiongkok tidak dan tidak akan menghormati mereka – jika saja dunia mau mendengarkan.”